SINESTESIA: Antarkan Saya Pulang
“Habis bulan puasa,” atau “Tahun depan.” Itulah
kalimat yang selalu terlontar dari personel Efek Rumah Kaca. Entah sejak tahun
berapa. Omongannya bukan kosong, tetapi memang selalu ada yang keluar, entah
Pandai Besi, ERK Remix, kolaborasi dengan musisi lain, merchandise, konser PanBes. Biar, sampai lelah untuk menanyakannya
lagi karena terus merasa diakal-akali, celaan yang menghantui malah menjadi
hambar saking lamanya. Sebenarnya, ini bukan hanya perkara celaan yang jadi kartu
kunci, saya juga menanti betul-betul album ketiga Efek Rumah Kaca.
Penantian terjawab dengan album yang
dipirit-pirit. Satu single, satu single, konser di Bandung—yang tidak
bisa ditonton karena saya sedang ada di Belanda. Saya sudah mempersiapkan diri
untuk dua single yang siap diramu
Pandai Besi, tapi ternyata tidak bisa setertebak itu. Satu album penuh keluar.
Beberapa hari setelahnya, saya membeli melalui iTunes. Sekalinya transaksi
pakai kartu kredit, tagihan muncul 600-sekian ribu. Saya kira album Sinestesia ini seharga demikian, tapi
setelah ditilik lebih lanjut, transaksi saya dibajak dan berakibat penutupan
kartu kredit setelah membeli album digital Sinestesia.
Tanpa menyalahkan karena tidak ada hubungannya, saya mendengarkan Sinestesia sebagai musik latar belakang:
sambil mengetik, bekerja, browsing, bersih-bersih kamar, naik sepeda,
berbincang dengan teman-teman, main capsa. Sekian hari, saya mulai mengganti playlist. Tanpa memperhatikan liriknya.
Tanpa memperhatikan musiknya. Sinestesia
membosankan. Pernyataan serius.
Tapi, tapi, tapi, hari ini, saya berubah pikiran.
Pernyataan yang jauh lebih serius. Sinestesia bukan “musik sembari”. Dalam
perjalanan dari Maastricht ke Den Haag selama lebih dari 3 jam, saya
mendengarkan Sinestesia. Pengalaman
subjektif itu membuat saya merasa perlu mematahkan gengsi berlapis-lapis dengan
mudah. Subjektif menjadi begitu penting karena, toh, lagu bisa berarti berbeda
bagi setiap orang. Maksud dari pengarang lagu dipinggirkan tanpa dihilangkan.
Ini bukan menegaskan “pengarang sudah mati” yang rasanya sudah basi. Bagaimana
mungkin pengarang bisa mati setelah menciptakan? Kebebasan
menginterpretasikannya bukan mematikan pengarang. Iya, saya menyanggah omongan
saya sendiri pada masa lalu. Pengalaman subjektif begitu penting; personal is political.
Saya
Takut untuk Pulang
Untuk menceritakan pengalaman subjektif, saya
perlu memberikan gambaran konteks. Kurang lebih saya tinggal di Belanda selama
1,5 tahun. Dalam waktu kurang dari seminggu, saya akan kembali ke Jakarta.
Bukan untuk 3 hari, bukan untuk 1,5 bulan, tapi menetap di Jakarta yang
kemungkinan besar bertahun-tahun. Saya akan melewatkan banyak hal, termasuk
konser Sinestesia. Rasanya, lebih
banyak lagi yang sudah saya lewatkan. Saya ingin pulang, tidak meragukan itu
sama sekali. Tapi, keinginan bukan tanpa ketakutan. Ketakutan meninggalkan
kehidupan di Belanda—semacam kehidupan pelarian—memang ada, tapi ternyata
sedikit. Saya merasa lebih didominasi oleh perasaan ketakutan untuk kembali ke
Jakarta. Saya takut merasa kesepian. Lebih menyeramkan merasa kesepian di kota
yang dipenuhi orang-orang yang saya kenal. Juga, ketakutan untuk tidak bisa
memenuhi harapan orang-orang, semudah takut tidak bisa memberikan jawaban
menarik ketika ditanya: “Bagaimana Belanda?”, takut tidak bisa menyesuaikan
diri dengan lingkungan yang sudah punya kebiasaan dan obrolan baru, takut tidak
bisa menahan diri untuk mengeluh, tidak bisa berhenti bernostalgia dengan
memulai segalanya dengan “Waktu gue di Belanda,…”—yang selalu saya keluhkan
dari orang-orang yang pernah tinggal di luar negeri, takut bingung, takut
ketinggalan. Saya tahu ini bentuk insecure
saya. Saya juga sadar bahwa insecure
milik masing-masing dan saya tidak bisa meminta pertanggungjawaban orang lain
atas rasa insecure saya, juga tidak
mau menjemukan orang dengan cerita ketakutan akan sesuatu yang belum terjadi.
Tapi, takut boleh saja, kan? Dan, kalau diingat-ingat, banyak hal dimulai
dengan ketakutan dan berakhir baik-baik saja, bahkan mengesankan.
Sinestesia:
Warna-warni yang Memusat
Bayangkan satu adegan dalam film ketika ada
seorang perempuan yang duduk di sebelah jendela di kereta. Melempar pandangan
ke luar, memerhatikan pepohonan yang seakan berlari juga hamparan rumput.
Sesekali ia menulis, sesekali ia menyeka air mata. Sayangnya, ini bukan adegan
film yang memaklumi segalanya. Saya melakukannya sambil malu-malu mengelap air
mata dengan syal.
Selama di perjalanan kembali ke Den Haag, saya
banyak berpikir tentang kepulangan saya ke Jakarta. Saya memilih Sinestesia untuk menjadi lagu pengantar.
Bukan lagi sebagai musik latar atau musik sembari, tapi benar-benar
mendengarkannya kali ini. Dan, sialan. Sinestesia
ini brengsek. Ini gambaran dari saya.
Sinestesia
ini begitu personal. Tragis.
Kejujuran yang menyakitkan sekaligus menyadarkan. Sesuai dengan urutan lagu
dalam albumnya, ia mulai dari lapisan terluar yang berbicara tentang segala
yang di luar. Kemudian, ia bergerak menyerang diri sendiri, mengais
pertanyaan-pertanyaan dalam diri sendiri yang sudah ditimbun. Sinestesia menggalinya kembali. Hingga
ditutup oleh lapisan terdalam. Sesuai liriknya—tanpa melihat di laman mereka,
sesuatu yang bersemayam. Ini gambaran absurdnya, saya mencoba membuka lapisan
bawang terluar dan melanjutkannya ke lapisan-lapisan selanjutnya.
Merah.
Kerja Keras.
“Merah” mengantarkan saya untuk melakukan sesuatu
sepulangnya di Jakarta, melanjutkan apa yang belum selesai, melakukan apa yang
belum dimulai. Meyakinkan saya untuk tidak membiarkan segala kekarut-marutan,
pun bukan serta-merta membenahinya. Juga bukan serta-merta merasa berani, tapi
juga dipenuhi keraguan. “Sampai kapan kau
ikhlaskan dia dihancurkan.”
Terbersit juga dilema posisi yang kadang disebut
dengan kemunafikan. Padahal, kadang itu adalah kejujuran. Apakah menjadi jujur
kemudian bisa disebut sebagai munafik? Misalnya, “Politik terlalu iblis dan kita teramat manis.” Ada dilema
fleksibilitas identitas yang sebenarnya begitu wajar: memperjuangkan sesuatu
yang dianggap baik; sok-sok idealis tanpa menghasilkan apa-apa; sok-sok idealis
tapi lemah kalau harus adu argumen. Ketika ingin melakukan sesuatu yang dianggap
baik, tetapi disebut-sebut sebagai cita-cita utopis. Lagu ini mengukuhkan hati
bahwa ada tujuan yang ingin dicapai, pun dalam perjalanannya, tentu banyak
tantangan. Tapi, tidak ada yang sia-sia, bukan? Mungkin itu pertanyaan sebagai
pembenaran yang kerap saya ulang dalam menghadapi kepulangan.
Pada menit ke-07.25, saya merasa musiknya lebih
seperti bermain-main. Saya membayangkan jika lagu ini dibawakan di panggung,
penonton akan turut bernyanyi beramai-ramai mulai dari, “Moralis merasa yang paling baik….” Bagi saya, “Merah” bukanlah
penilaian berlebihan terhadap sesuatu yang ada di luar diri, bukan tentang
orang lain, tetapi mempertanyakan diri sendiri. Mempertanyakannya tanpa maksud
menyerang diri sendiri; pertanyaan yang seakan mengajak bermain. Apakah kita
moralis? Apakah kita sang martir? Apakah kita fatalis? Mungkin, memang benar, “mukzizat hanya ada di zaman nabi”, kita
perlu kerja keras. Lebih keras.
Biru. Harapan.
“Biru” menawarkan harapan bahwa banyak hal bisa
dilakukan. Keoptimisan yang ditawarkan seakan menjadi ajang cuci otak dengan
mengulang-ulang “pasar bisa diciptakan”.
Meyakinkan. Setelah pengulangan itu, dentuman bas menjaga semangat, juga diisi
oleh melodi gitar. Semakin meyakinkan. Bagian ini meningkatkan semangat yang
terwakilkan melalui tepuk tangan berirama. Musiknya festive. Ada echo yang
memperkuat ketika “Dari kegelisahan
dipadatkan dengan cinta” dan “Fantasi
yang menggila bercampur rasa kecewa”. Bagian lirik itu juga tetap
mengingatkan keadaan realistis. Tidak berhenti di situ, dilanjutkan dengan, “pelan-pelan hilangnya jadi percik cahaya.”
Setelah dibanting dengan keadaan realistis, “Biru” mencoba mengangkat lagi
emosi saya. Saya merasa sedang berbincang dengan orang tua yang sedang
memberikan nasihat, “Hidup itu tidak mudah, Nak, tapi tetap indah.”
Masuknya vokalis perempuan pada menit ke-08.15,
“Kegelapan masih membayang, menyelimuti, menolak pergi…”, diikuti dengan
dentuman drum dan masuklah terompet. Suasana festive meningkat. Bagian ini berakibat fatal pada saya, meyakinkan
bahwa akan banyak keadaan yang tidak ideal, tetapi kadang kita perlu menjalani
keadaan paling mending dari yang terburuk, sesuatu yang setidaknya masih bisa
dijalankan, sekaligus bahwa ada kesalahan yang akan dijalani dengan penuh kesadaran.
Sepulangnya nanti, mungkin saya kerap bilang, “Saya tahu ini tidak ideal, tapi
ini adalah cara yang setidaknya masih bisa dilakukan.”
Jingga.
Ketakberdayaan.
Lagu ini—atau potongannya—pernah dimainkan sewaktu
saya masih di Jakarta. Lupa tepatnya. Begitu mendengarkan lagu ini, saya
mengingat momen saya sewaktu menghadiri International People Tribunal di Den
Haag beberapa bulan lalu. Lirih. Kesaksian-kesaksian yang diungkapkan langsung
di hadapan jauh lebih menyelekit dibanding cerita-cerita serupa yang pernah
diceritakan kembali oleh orang lain, lebih parah daripada kisah di dalam
buku-buku tentang 1965. Cerita kepelikan semacam itulah yang tak akan pernah
bisa ditertawakan. Akhirnya, saya menemukan kepelikan yang tidak layak untuk
dirayakan. Pada saat yang sama, saya mengingat ketakberdayaan saya. Perih,
tanpa bisa melakukan apa-apa. Tertekan karena merasa tidak berdaya. Kenyerian
itu diperparah oleh penyebutan nama-nama orang yang hilang. Dan, dipertegas
dengan “Hilang”. Belum selesai
mengiris-ngiris, vokalis perempuan memperkuat kelirihan. Layaknya tangisan ibu.
“Jingga” juga mengingatkan saya akan pertanyaan
apakah—misalnya—Munir setiap hari bangun tidur dan ingin menjadi pejuang? Atau,
apakah ia—dan juga mereka—hanya ingin melakukan sesuatu yang benar? Atau baik?
Tapi, Pramoedya pernah bilang, “baik belum tentu benar”. Bukankah kegelisahan
itu memang akan terus membayangi kita?
Denting piano yang ‘ketinggalan’ itu semakin membuat
lagu ini brengsek—dentingan ini berbeda dengan versi sebelumnya yang pernah
saya dengar, rasanya. ‘Ketinggalan’ itu seakan meninggalkan jejak memori. Tidak
pernah tahu kapan selesai, banyak hal yang dikira sudah selesai, ternyata
belum. Dan, tidak tahu kapan pernah selesai. “Yang hilang berganti hingga tak terbilang.”
Hijau.
Kejujuran.
“Hijau” menegaskan ketakutan saya untuk pulang
layaknya tamparan berulang kali pada tataran wacana. Saya menangis
sejadi-jadinya ketika mendengarkan lagu ini, sesunggukan. Lirik dimulai sejak
detik pertama, tanpa basa-basi. Kejujuran perih langsung dihantamkan, “Apa yang kau tawarkan bukan pengetahuan?
Ucapan miskin pemikiran. Apa yang kau sodorkan hanyalah hasutan, ujaran penuh
kemunafikan.” Lagiu ini memperkuat ketakutan saya yang merasa tidak bisa
menjawab ekspektasi orang-orang kepada saya sepulangnya nanti. Saya merasa
belum apa-apa, bahkan saya merasa semakin tidak paham. Pengakuan terhadap diri
sendiri yang masih culun punya.
Tidak hanya membanting—atau bahkan mendorong dari
ujung tebing, “Hijau” juga mencoba menawarkan sesuatu. Bukan solusi, hanya
tawaran cara. “Dipilah, dipisah, agar
gampang diubah, biar mudah diolah.” Segala kekacauan pemikiran yang
dipenuhi dengan asumsi-asumsi yang hampir menjadi fakta sebaiknya dilerai satu
per satu untuk melihat kembali kesalahan kerangka berpikir. Tapi, untuk bisa
seperti itu, tentu perlu berpikir. Dan, saya seringnya malas untuk berpikir.
“Hijau” menawarkan tujuannya, semalas apapun, itu perlu dilakukan agar bisa
diubah. Mengakui kesalahan berpikir, pemaksaan nilai-nilai terhadap orang lain.
Putih. Kematian.
Kepergian saya ke Belanda diiringi dengan keadaan
kesehatan ayah yang sedang dalam keadaan tidak sehat selama beberapa tahun
terakhir. Ini adalah keadaan yang sempat membuat saya ragu sampai akhirnya ayah
menyatakan langsung untuk memberkati kepergian saya ke Belanda. Saya selalu
dipenuhi kekhawatiran jika ada pesan dari rumah, terus memastikan keadaan
baik-baik saja. Suatu waktu, ayah pernah sakit, sesak napas. Ternyata, ia tidak
minum obat selama dua hari. Padahal, ada belasan obat yang harus diminumnya
setiap hari. Saya teringat omongannya sewaktu saya di Jakarta. Ia mengeluhkan
hidupnya yang mahal. Ia harus mengeluarkan uang berjuta-juta setiap bulan untuk
menyambung hidupnya hanya dengan obat. Saya merasa sakitnya ketika itu
merupakan cara dia untuk berkompromi terhadap tubuhnya dan juga keadaan, dan
berujung tidak ada jalan tengah. Tidak mudah untuk mengakui ini: saya sering
membayangkan kematian ayah saya. Kacau, memang. Saya melakukannya untuk merasa bisa
mempersiapkan diri. Bahkan, saya selalu menyisihkan sebagian uang yang siap
dipakai untuk membeli tiket pulang sewaktu-waktu. Jadi, ketika “Putih”,
meledaklah tangis saya. Lebih-lebih dari “Hijau”. Apakah saya bisa semenerima “Putih”
dalam menghadapi kematian?
Petugas kereta menangkap saya sedang menangis. Ia
menghampiri saya dan meminta saya untuk pindah kereta karena kereta ini
ternyata tidak akan berjalan ke mana-mana lagi; meneteap di Eindhoven. Saya
orang terakhir yang masih di kereta. Saya melupakan keadaan sekitar, ternyata.
Saya melanjutkan mendengarkan “Putih” dalam
perjalanan kereta setelahnya menuju Den Haag. Pada menit ke-05.03, saya
merasakan lirihan ibu saya. “Selamat
datang di Samudra, ombak-ombak menerpa” mengantarkan saya untuk melihat
Tuhan. Saya berkali-kali menulis surat kepada Samudra, yang sebenarnya saya
asosiasikan dengan Tuhan. Bagian favorit saya, “Rekah, rekah, dan berkahlah”. Mungkin, maksudnya, bagian ini
diperuntukkan bagi anak-anak yang menjadi harapan. Bagi saya, bagian ini
diperuntukkan bagi orang-orang yang ditinggal kematian. “Putih” meyakinkan saya
untuk pulang. Karena ayah, adalah motivasi utama saya untuk pulang.
Kuning.
Ketuhanan.
Selama di Belanda, saya merasa lebih mengenal diri
saya sendiri. Tidak mudah mengakui banyak hal tentang diri saya. Misalnya saja,
kesadaran bahwa saya tidak sepenuhnya atheis. Saya masih percaya tentang energi
besar, mempersonalisasi Tuhan. Menjalani kehidupan bukan atas nama ketakutan
akan neraka atau pencapaian surga. Menjalani kehidupan dengan proses pencarian
akan kebenaran, termasuk kesalahan, juga di antaranya. Kadang, kebenaran
diketahui setelah kesalahan. Pun, saya sebenarnya menghindari gila-gilaan
oposisi binari.
“Kuning” menemani saya untuk berbicara dengan Samudra.
Dentingan piano yang aduhai nian. Bukan dengan alunan musik yang melirihkan,
tapi justru menciptakan suasana keramaian yang tenteram ketika “Bila matahari sepenggal batasnya…” Ini
adalah bagian gebukan drum favorit saya. Keikutsertaan vokal-vokal lain
memberikan suasana penuh suka-cita sekaligus temaram. Dan, semenit terakhir
mengingatkan saya akan keadaan rumah. Saya mau pulang.
Selamat konser, Efek Rumah Kaca.
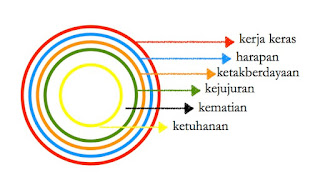
Komentar
Posting Komentar