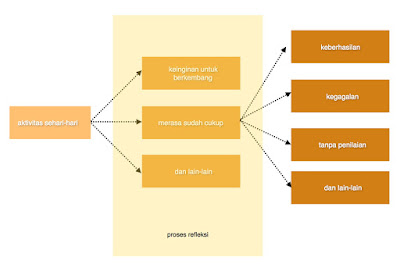Amer Bersama Amal #1: Waktu di Belanda
Saya suka minum wine. Ini dimulai waktu saya sekolah di Belanda dulu. Wine di sana enak. “Semua hal yang dari Eropa itu enak,” kata teman saya. Itu bohong besar. Nggak semua hal—termasuk pemikiran—dari Eropa itu enak. Makanan, contohnya. Makanan mereka nggak ada rasanya. Buat saya, rasanya hambar. Roti dingin, daging dingin, dan keju dingin untuk makan siang. Beda dengan rendang atau gulai di rumah makan padang. Tapi, saya memang selalu makan di tempat-tempat yang sebisa mungkin tidak mengeluarkan uang, sih. Rumah dosen, tempat teman, dan masakan saya sendiri. Jadi, argumentasi saya juga payah. Bisa jadi, masakan dosen saya atau teman saya saja yang rasanya kurang enak. Kalau masakan saya, itu hampir pasti. Hampir pasti tidak enak. Mungkin memang ada makanan Eropa yang enak. Saya cuma nggak mampu beli saja. Atau, saya nggak diundang ke rumah dosen lain yang masakannya lebih enak. Atau, saya memang nggak punya teman lain yang masakannya enak. Mereka nggak masak,