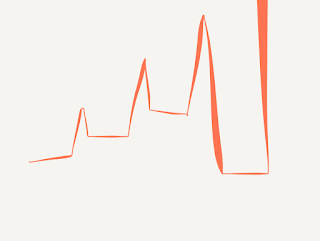Merangsang Kekhawatiran
“Ini pertunjukannya interaktif, nggak?” “Maksudnya?” Pertanyaan saya ajukan dengan alasan antara tidak mengerti, menanyakan ulang maksudnya sama dengan yang saya tangkap atau bukan, atau memastikan ia bicara dengan saya. Atau, saya mungkin tidak mendengar jelas dia bilang “penunjukan” atau “pertunjukan” dan hasrat untuk menyunting besar. “Akan ada interaksi antara pemain dan penonton, nggak? Saya duduk di paling depan, nanti bisa ditanya-tanya. Saya takut.” Perempuan itu duduk di depan saya. Kami sudah duduk manis di bagian kanan panggung jika menghadap ke ruang suara di depannya. Ia tidak sendiri, bersama pasangannya. Saya juga. Maksudnya, saya juga tidak sendiri, bersama teman-teman saya di kiri dan kanan saya. Saya memajukan badan saya untuk memastikan kursi di sebelah kirinya masih kosong. “Di sebelah ada orang?” “Nggak ada.” “Wah,” Begitu saja saya merespons. “Oh iya! Jangan-jangan, pemainnya duduk di sini.” Dahinya berkerut. Mulutnya terbuka sedikit. Matanya sed