EITS: Tahu Makna Cukup
Ini adalah
satu-satunya—sampai saat ini—band favorit
yang saya tonton konsernya dan saya tidak berharap ada encore. Cukup. Bahkan, saya memohon dalam hati—yang tiada gunanya
itu—jangan sampai ada encore. Mungkin
kebetulan, mungkin semesta berbicara, mungkin juga tidak ada hubungannya sama
sekali, malam itu, Jumat, 3 Maret 2017, tidak ada lagu tambahan setelah momen
dramatis penutup lagu dari Explosion in the Sky. Dada saya sudah tidak muat
lagi.
“The Only Moment When We
Were Alone” menjadi lagu penutup. Lagu yang satu ini memang bukan kepalang.
Judulnya sendiri sudah bicara banyak. Rangkaian melodi yang ditawarkan pun
bertahap. Tahapannya terasa betul. Kurang lebih, bagi saya, grafiknya begini.
Penghujungnya, ketika
tempo sedang cepat-cepatnya, rasanya sedang klimaks-klimaksnya, mereka berhenti
seketika, bersamaan. Lampu di panggung semua padam. Gelap. Mereka tidak
terlihat sama sekali. Ada, tetapi tidak terlihat. Pertunjukan selesai. Mereka
tahu apa artinya kata cukup dan menjalaninya dengan baik. Sangat baik.
Grafik-serupa-beda-ujung
sebenarnya juga bisa menggambarkan lagu-lagu Explosions in the Sky yang
dimainkan malam itu. Bagi saya, kebanyakan lagu mereka memang begitu. Ini
terasa betul waktu di “First Breath After Coma”. Ketika sedang cepat dan naik,
cepat dan naik, sekali lagi—cepat dan naik, saya merasa diajak masuk dalam ke-chaos-an yang terasa benar dan betul. Chaos
yang bijak. Kekacauan yang memang dibiarkan. Pada saat genting-gentingnya, tiba-tiba
dentuman drum menghilang, dentingan gitar memainkan bar yang sama beberapa kali
dengan lambat. Jauh lebih lambat. Sabar. Saya serasa diajak untuk turut sabar.
Sabar yang menyenangkan, jauh lebih tepat: menenangkan.
Saya merasa tenang karena
dikelilingi oleh sound mereka. Ini dia salah
satu yang berbeda dari mendengarkan mereka melalui speaker atau headset.
Suaranya bukan hanya bersahut-sahutan di kuping kiri-kanan, tetapi ketika menontonya langsung, suaranya ada di sekeliling tubuh. Sound-nya terasa memutari saya, tetapi
hanya di bagian dada; tidak pinggang ke bawah. Itu membuat saya merasa
mengambang. Ditarik ke galaksi. Gelap, tetapi ada banyak cahaya bintang. Oh,
cahaya.
Dan, dan, dan, suasana
diperkuat dengan lighting yang
menegaskan bahasa musik Explosions in the Sky. Misalnya, ketika lagu-lagu
mereka di awal—contohnya adalah lagu “The Birth and Death of the Day”—sedang melambat,
mereka cenderung pakai lampu-lampu monocolor yang redup. Semakin lama, warna lampu mulai dipadu-padankan.
Namun, metodenya serupa. Lampu-lampu itu ditembakkan ke bagian belakang mereka
sehingga siluet mereka terlihat dengan asap-asap yang sengaja meramaikan
panggung. Smokey silhouette. Bahkan,
ketika “Colors in Space”, panggung begitu gelap pada saat-saat seperti ini.
Masuk ke bagian “chaos bijak”
tersebut, lampu lebih gelap. Kemudian, disambung dengan apa? Cahaya putih yang
menyilaukan; tepat ketika tempo langsung begitu lambat. Terang. Sabar yang
seakan membuahkan terang.
Pun, ketika membaca banyak
komentar para penonton konser Explosions in the Sky di satu negara ke negara
lain, pada satu tahun ke tahun lain, “smokey
silhouette” memang jadi kebiasaan mereka. Bisa jadi, ini adalah bentuk
konsistensi mereka dalam merepresentasikan bahasa musiknya; tanpa visual
apa pun di belakangnya. Kemudian, mereka bisa menganggap, “Ini sudah cukup”
yang kemudian menjadi ciri khas mereka. Atau, ini bisa jadi peluang monoton
yang sudah tertebak bagi fans garis keras yang hadir di konser mereka
berkali-kali. Tidak ada kebaruan yang ditawarkan. Apa pun alasan mereka, bagi
penonton first timer seperti saya,
saya rela melihat itu lagi.
Satu hal yang penting
untuk dicatat adalah semua ironi tersebut nyaris tidak diberi jeda sama sekali.
Dari satu lagu ke lagu lainnya, semua nyaris dijahit dengan distorsi. Entah apa
itu distorsi. Antarlagu dijahit tanpa diam. Tanpa kata. Tak ada satu kata
pun yang diucapkan mereka sejak set dimulai.
Saya tidak diberi waktu sedikit pun untuk sekadar menghela napas. Intense. Padahal, saya merasa perlu jeda sekejap
saja untuk melepaskan apa-apa yang masuk ke dada sejak set dimulai. Dada mulai
sesak. Mungkin, istirahat hanya diperuntukkan siapa-siapa yang lemah, seperti
saya. Explosions in the Sky seperti tidak mau kehilangan frekuensi yang sudah
terbangun sejak awal di antara mereka. Diperkuat terus tanpa ampun hingga 11
lagu sampai selesai, tanpa membiarkan jeda mengganggu frekuensi yang sudah
tersimpul.
Konser Explosions in the
Sky mematahkan asumsi saya. Selama ini, saya sering beranggapan bahwa lagu-lagu
mereka adalah lagu privat. Maksudnya, cocok untuk dinikmati sendiri atau
berdua-bertiga yang sedang minim pembicaraan. Bukan diam karena kaku, tetapi memang
memilih untuk diam. Explosions in the Sky cocok untuk situasi seperti itu.
Menikmati apa yang ada dalam kepala. Asumsi payah itu membuat saya lebih sering
menikmatinya ketika sendirian. Satu asumsi membawa asumsi lainnya—tak pernah
bisa sendirian si asumsi, saya punya cara sendiri untuk menikmati lagu mereka.
Bukan sekadar head banging, tetapi
menari semaunya. Sendirian. Di ruang tengah, di mobil, di kamar mandi. Namun,
asumsi itu memang patut dan layak dipatahkan.
Malam itu, orang-orang
sekitar saya menari. Bukan sekadar mengikuti irama sambil mengangguk-anggukkan
kepala, menepuk-nepuk paha dengan tangan, atau mengangkat ujung sepatu berulang
kali dengan posisi tubuh terlihat cool seperti
yang sering terlihat di gigs-gigs Jakarta.
Kami menari dalam artian menggerakan seluruh tubuh, bahkan pasangan yang ada di
beberapa baris depan saya, mereka berputar-putar. Saya baru sadar bahwa
lagu-lagu semacam Explosions in the Sky memang bisa dinikmati dengan cara yang
jauh lebih menyenangkan. Kalau sendirian saja menyenangkan, apalagi kalau bisa
melakukannya bersama-sama? Saya ingat betul pada “Disintegration Anxiety”, crowd di sekitar saya menari
semenari-menarinya. Memang, kalau diperhatikan, beberapa saf di sebelah kanan,
mereka masih penonton cool yang merasa
cukup dengan mengangguk-anggukkan kepala tadi. Tapi, tidak apa-apa. Setiap orang
punya cara menikmati musik yang berbeda. Untungnya, saya yang berdiri di tengah
baris ketiga dari depan bagian tiket reguler dikelilingi oleh orang-orang yang
bisa menikmati serupa dengan cara saya tanpa malu-malu.
Ketika lampu sedikit
terang, kami—para penonton yang tidak saling kenal—bahkan saling melempar
senyum. Kalau mengenal, ketika sedang meluap-luap dan sudah mulai tumpah ruah,
kami berpelukan. Saya memeluk beberapa kali. Juga dipeluk beberapa kali. Dan,
ini bukan hanya kami. Saya melihat dua orang yang berdiri di baris paling depan
berpelukan sambil berteriak. Saya rasa, kebanyakan dari kami punya kesamaan.
Tidak sanggup menahan kebahagiaan sendirian. Crowd semacam ini lah yang membentuk pengalaman menonton Explosions
in the Sky juga terasa beda.
Setelah panggung mendadak
gelap di penghujung, dengan lampu masih sedikit redup, Munaf menutup set leaderless band ini, seperti klaim
mereka—tapi band mana yang mengaku
punya leader? Saya kira,
Hrasky lah yang akan banyak bicara, seperti salah satu laporan konsernya di
negara asal mereka. Namun, saya harus mematahkan asumsi yang kurang berdasar. Munaf
bilang terima kasih dan senang bisa main di Singapura, juga crowd yang menyenangkan. Standar omongan
musisi yang lihai membuat senang penonton. Padahal, itu bisa jadi sudah template. Set juga dibuka—setelah
Unknown Mortal Orchestra bermain sebagai band
pembuka—oleh Munaf yang mengenakan kaus. Ya, malam itu, mereka semua pakai
kaus. Konon, di konser-konser lain, mereka juga biasa pakai kaus. Kadang,
mereka pakai kemeja polos atau kotak-kotak.
Kalau diingat-ingat, perkenalan saya dengan Explosions
in the Sky dimulai sekitar 2004 melalui lagu-lagu yang dibuat setelah tur mereka: “Day
1” sampai “Day 6”. Saya jatuh cinta karena ketukan drum-nya. Hrasky lah yang saya perhatikan sejak awal. “Day 6”
adalah favorit saya. Malam itu, mereka sama sekali tidak memainkan lagu-lagu
dari album itu. Saya tidak apa-apa sama sekali. Begitu saja sudah cukup. Kalau
sudah cukup, kenapa harus ditambah lagi? Saya belajar dari Explosions in the
Sky soal cukup yang kadang masih belum bisa dijalankan dengan baik. Yang penting,
belajar dulu. Padahal, di album itu, ada “Day 3” yang merupakan satu-satunya
lagu mereka yang ada orang berbicara—dari yang sudah pernah saya dengar. Apa
bisa disebut lirik? Saya kira tidak. Itu lebih terdengar mereka sedang bertukar
cerita tentang tur mereka dan memutuskan untuk memasukkannya dalam satu lagu
itu. Kata teman saya, di Kaskus, ada
satu orang yang menyalin percakapan mereka. Saya sendiri belum cek.
Explosion in the Sky
memang hanya bicara melalui judul dan instrumen musik. Tapi, cukup. Begitu
saja, dada saya terlalu penuh. Mungkin benar, saya tidak tahu bagaimana caranya
mengatasi kebahagiaan. Dan, malam itu, saya bahagia sekali.
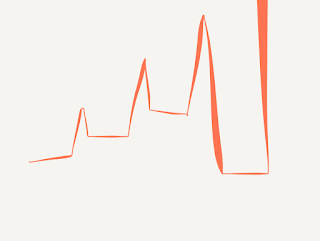

Komentar
Posting Komentar