Benalu Publik
Apa
keberhasilan Anda selama seminggu terakhir?
Pertanyaan tersebut sering saya tanyakan dalam pelatihan, lokakarya, atau bentuk forum lainnya. Sering kali, kita* mengalami kesulitan menjawab itu. Kita malah cenderung lebih mudah menjawab pertanyaan, “Apa masalah yang Anda hadapi selama dua hari ke belakang?”
Kita menganggap keberhasilan sebagai suatu hal yang begitu besar. Prestasi. Penuh perjuangan. Keseharian kita tidak dianggap sebagai bentuk keberhasilan-keberhasilan kecil yang mengajak kita menuju sesuatu yang lebih besar. Lagipula, apa pula yang membuat besar terasa lebih adekuat?
Kita menganggap keberhasilan memberikan pengaruh terhadap banyak orang. Kesibukan setiap hari dianggap miskin pengaruh. Apakah memberikan ASI setiap hari tidak memberikan pengaruh terhadap anaknya? Apakah berkata dan bertindak jujur setiap hari tidak memberikan pengaruh terhadap orang-orang yang kita temui?
Mengaku-aku
keberhasilan merupakan bentuk dari kepongahan. Dan, kita diajarkan di sekolah
dan di rumah untuk menjadi rendah hati. “Jangan sombong. Tetap rendah hati,“
begitu pesan ibu atau bapak.
Kita
begitu khawatir mengakui keberhasilan karena takut merasa puas dengan keadaan
sekarang dan tidak ada keinginan untuk mengembangkan diri lagi. Wong, begini
saja sudah cukup, lantas buat apa melakukan lebih?
Apakah
selalu demikian? Menurut saya tidak. Justru, semua anggapan itu begitu berisiko terhadap
mutu kehidupannya sebagai manusia.
Mengakui
keberhasilan bukan serta-merta menjadikan kita menjadi jemawa. Malah, mengakui
keberhasilan merupakan salah satu tanda bahwa kita melihat kembali apa-apa saja
yang telah dilakukan dalam hidupnya. Orientasinya bukan pada masalah, melainkan
keberhasilan-keberhasilan kecil. Bisa jadi, ia malah tertantang untuk melakukan
sesuatu yang lebih baik. Memang, memang, tidak semua orang begitu.
“Saya
tidak menggunakan sedotan plastik hari ini.”
“Saya
tidak membeli barang yang tidak saya perlukan, meskipun saya menginginkannya.”
“Saya
mengirim pesan kepada ibu saya untuk menanyakan kabarnya.”
“Saya
membaca beberapa artikel tentang isu yang saya tekuni.”
Keputusan-keputusan
tersebut tidak dinilai sebagai keberhasilan karena seakan hanya aktivitas
sehari-hari. Tidak ada perjuangan yang signifikan dibandingkan orang-orang yang
susah payah bertahan hidup. Apakah kita selalu menilai kehidupan kita dari
kacamata orang lain?
Menurut
saya, bukan keberhasilan yang menakutkan bagi kita, melainkan alasan di
belakangnya.
Ketiadaan
keinginan untuk berkembang.
Ini
bisa menjalar ke mana-mana.
Egocentric.
Alih-alih
rendah hati, kita menganggap tidak memberikan pengaruh apa-apa. Kita merasa
keputusan—yang dianggap—kecil tidak akan mengubah sistem yang sudah semrawut.
“Kalau saya membuang sampah kertas sembarangan, itu tidak akan berpengaruh
terhadap lingkungan. ‘Kan cuma satu orang.” Kita tidak merasa hidup sebagai
bagian dari publik. Padahal, bukankah cukup jelas bahwa perilaku satu orang
berpengaruh terhadap orang lain ataupun lingkungannya? Apakah kita harus mengubah
orang lain ketika melakukan sesuatu? Bukankah perubahan dimulai selalu dalam
diri kita sendiri? Ya, ya, ya, ini seperti kutipan-kutipan dalam Instagram.
Tidak profesional.
Karlina
Supelli pada 2013 bilang bahwa profesi merupakan bentuk janji publik.
“Seseorang disebut profesional bukan terutama dia pakar di bidangnya, melainkan
karena dengan kepakarannya, dia menjalankan tugas dan pada saat bersamaan dia
menjadikan keahliannya sebagai sumbangan hidup bersama.” (hlm. 91)
Saya
sadar, kita bisa merasa sudah melakukan sumbangan yang berdampak ketika ada
respons dari orang lain.
Apakah
Anda selalu memberi tahu orang lain yang omongannya Anda kutip? Apakah Anda
selalu mengirimkan surat kepada orang-orang yang ternyata memberikan inspirasi
atau setidaknya penggugah pikiran Anda?
Tanggapan
sering kali dilakukan diam-diam. Tanpa kita tahu.
Apakah
kita melakukan sesuatu untuk melulu dianggap oleh orang lain dan bukan karena
kita sendiri?
Saya
tidak menampik kebutuhan untuk pengakuan eksistensi di hadapan orang lain.
Hanya saja, itu tidak perlu menjadi selalu atau melulu.
Mandek.
Otak
kita berada dalam status pause. Berhenti.
Pikiran
kita tidak awas akan informasi yang kita terima untuk bisa digunakan sebagai
bahan bakar aktivitas. Motif kita untuk melakukan sesuatu hanya berdasarkan
target semata, impian karier. Kita terlalu takut untuk melakukan kesalahan
karena kita tahu akan dinilai. Dan, biasanya oleh perusahaan. Atau, sayangnya,
juga oleh organisasi—yang katanya beralaskan—kemanusiaan.
Otak
kita tidak ada dalam keadaan haus akan pengetahuan dan berpikir kritis.
Biasanya, kita bisa merasakan ini ketika memang dalam proses belajar. Ada
keinginan untuk mengembangkan diri. Coba tonton video
TedEx yang bicara soal ini.
Itu
semua bukan berasal dari pengakuan terhadap keberhasilan. Tapi, hal-hal yang
melandasinya. Bahkan ketika begitu rendah diri, ketiga hal itu justru bisa
mendasarinya pula.
Kita
ini merupakan bagian dari publik. Silakan tentukan sendiri publik yang mana.
Publik juga bukan satu entitas seragam.
Keputusan
hidup kita bisa saling berkelindan dengan kehidupan orang lain.
Contoh
dari luar Indonesia. Perempuan di Irlandia
bisa lebih mudah untuk mendapatkan akses aborsi aman karena advokasi yang
dilakukan orang-orang yang peduli. Keputusan mereka untuk meluangkan waktu dan
energi bisa berpengaruh terhadap kehidupan perempuan lain yang memang perlu
akses aborsi aman, misalnya.
Keputusan
orang untuk melakukan bom bunuh diri bisa berakibat pada kehidupan orang lain.
Mereka membatalkan
ibadah demi alasan keamanan. Bukan hanya di kota itu. Teman saya memutuskan
untuk tidak beranjak dari rumah karena rasa takut yang mencekam. Sangat masuk
akal.
Ketika
kita merasa tidak menjadi bagian dari publik yang bisa memberikan pengaruh,
mungkin perlu lihat daftar kemewahan yang kita kantungi. Mengeyam pendidikan
formal? Mempunyai uang yang cukup—mungkin sebagian lebih besar? Menjalani
pekerjaan yang akan diberi bayaran? Masih punya waktu luang yang cukup banyak?
Merasa tidak punya isu dengan kesehatan mental? Masih punya safety net
yang akan menampung kita ketika kesusahan?
Kemewahan
adalah bentuk kekuasaan atau kekuatan. Kita perlu sadar akan hal itu dan
membagi kekuasaan itu. Jika kita tidak membaginya, kita akan menjadi penguasa
yang tidak dermawan.
Kita
perlu memanfaatkan kekuasaan dengan melakukan sesuatu yang kita bisa sebagai
bentuk tanggung jawab sebagai publik dalam kehidupan sehari-hari. Foucault menunjukkan
hubungan antara kekuasaan-pengetahuan (teori dan praktik)-diri. Ketiganya
berkelindan. Pun tidak akan keluar dari kekuasaan dominan, tetapi dengan
mengetahui bagaimana kekuasaan bekerja dan menggunakannya untuk mengambil
keputusan, di situ lah letak kebebasan kita sebagai manusia. Foucault
mengatakan bahwa ini bukan perkara mencari kebenaran absolut, melainkan melerai
kekuasaan kebenaran dari bentuk yang hegemoni, sosial, ekonomi, dan kebudayaan
yang berlaku. Untuk melakukannya, kita bisa, setidaknya, berbuat sesuatu
sebagai bentuk sumbangan kepada publik.
Lerailah
kekuasaan dominan itu.
Kalau
pengetahuan Anda terkait dengan tulis-menulis, menulislah. Itu dibaca atau
tidak, urusan lain. Kalau belum ada yang membacanya, artinya Anda perlu
mengembangkan diri lagi. Pengetahuan dan keterampilan Anda. Tulis lagi. Tulis
lagi. Tulis lagi.
Saya
jadi teringat satu adegan dalam film The Young Karl Marx.
Seseorang mengatakan bahwa ia sudah membaca artikel yang disebutkan Marx. Di
situ, Marx dengan penuh kesatiran bilang, “Anda sudah baca? Kenapa tidak
menulisnya?” Nah!
Alasan
ketiadaan waktu hanyalah omong kosong. Kita harus memaksakan waktu.
Karlina
Supelli (hlm. 92) juga bilang, “ciri kematangan seseorang adalah ketika
dia sanggup melaksanakan suatu pekerjaan bukan karena dia suka, melainkan
karena dia berkomitmen.”
Komitmen
bukan hanya di atas kontrak kerja, apalagi surat nikah.
Apakah
kita perlu abai dengan omongan seperti ini?
“Saya
tidak perlu peduli karena saya tidak pernah merasakan itu. Hak asasi manusia
hanya untuk mereka yang membutuhkan. Apalagi feminisme.”
Itu
adalah tanda-tanda orang yang ngomong sedang melatih kekuasaan dan kekuatan
dengan cara yang berbeda dengan yang saya tuliskan di atas. Bersantai-santai
dengan kemewahan yang dimilikinya. Orang lain? Sekarep-nya.
Practicing
power.
Kekuasaan
bisa menjadikan Anda makhluk keji.
Berdarah
dingin.
Melakukan
kekerasan tanpa tangan yang penuh darah.
Tanpa
senjata.
Melainkan
diam-diam menjadi benalu yang mematikan tanaman tumpangannya.
Bacaan lebih lanjut:
Supelli, Karlina. (2013). “Kebudayaan dan
Kegagapan Kita” dalam Imajinasi Kebudayaan: Kompilasi Pidato Kebudayaan
Dewan Kesenian Jakarta 1998—2013. Penyunting: Mirwan Anda dan Martin
Suyajaya. Jakarta: Perhimpunan Koalisi Seni Indonesia.**
Foucault, Michel. (1980) Power/Knowledge:
Selected Interviews and Other Writings (1972—1977). Editor: Colin Gordon.
New York: Pantheon Books.
Tontonan lebih lanjut:
Eric Liu. “How to Understand Power” bisa
diakses melalui https://www.youtube.com/watch?v=c_Eutci7ack
*Saya menggunakan “kita” karena saya menjadi
bagian dari orang-orang yang saya kritik. Anda saya libatkan karena Anda mungkin juga
merasakannya; belum tentu.
** Saya juga menemukan Pidato
Kebudayaan Karlina Supelli ini yang diunggah oleh salah satu akun Facebook.
Saya belum berani untuk menyertakannya di sini karena belum meminta izinnya.
Artinya, Anda bisa mendapatkannya dengan mudah kalau mau mencari tahu lebih
lanjut.
-->
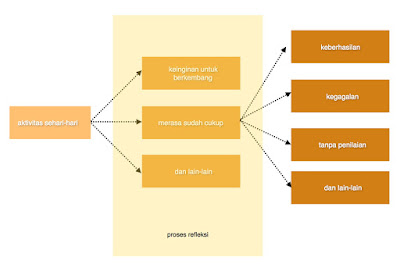
Komentar
Posting Komentar